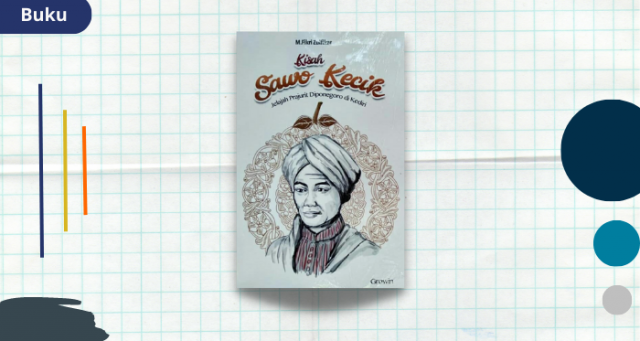Sawo adalah buah yang sering kita temui berdiri tegap di halaman rumah dengan lanskap pedesaan, yang seringkali pula dipanjati anak-anak kecil untuk bermain atau sekadar mengambil buahnya. Buah berwarna cokelat ini memiliki banyak varian jenis, tetapi terdapat satu sawo yang memiliki arti tersendiri bagi orang Jawa: sawo kecik.
Termasuk dalam tanaman yang memiliki nilai kesakralan bagi masyarakat Jawa, sawo kecik memiliki pelafalan yang hampir sama dengan ungkapan sarwo becik; yang berarti serba baik. Barangkali dalam sebiji sawo kecik terdapat harapan besar agar kebaikan selalu menyertai penanamnya, maupun pemakannya. Pasalnya, dalam segenggam sawo kecik ini terdapat khasiat di antaranya: menurunkan kolesterol, menurunkan darah tinggi, melancarkan BAB, dan lain-lain.
Selain memberikan khasiat kesehatan tubuh, buah yang memiliki nama latin Manilkara kauki ini ternyata juga pernah digunakan sebagai kode rahasia bagi laskar Diponegoro yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di bekas wilayah bang wetan dari Kasunanan Surakarta: Kediri.
Melalui buku ini, kita dipandu oleh Fikri Zulfikar untuk menapaktilasi jejak-jejak pasukan Diponegoro yang memilih menetap di wilayah Kediri: mulai dari timur, tenggara, sampai selatan. Buku berisi 28 sub-bab ini merupakan laporan jurnalistik yang diterbitkan dalam koran Jawa Pos Radar Kediri selama bulan Ramadhan pada tahun 2017.
Dalam tapak tilas Mas Fikri, terdapat beberapa ciri yang bisa diindikasi sebagai kediaman pasukan Diponegoro. Pertama, pohon sawo kecik yang ditanam di depan rumah atau masjid/musala.
Sebagaimana disebutkan di atas, pohon sawo kecik memiliki arti tersendiri dalam masyarakat Jawa, sebagaimana kedudukan pohon beringin. Kata “sawo” sendiri berasal dari “sawwu”, merujuk pada hadis Anas bin Malik: sawwu suhufakum, yang berarti “luruskan barisan kalian”.
Kedua, kelapa gading. Sebagaimana sawo kecik, kelapa gading juga ditanam di depan rumah atau masjid. Pohon yang memiliki ukuran lebih pendek dari pohon kelapa pada umumnya merupakan penanda bahwa di tempat tersebut digunakan sebagai pengajaran agama Islam. Ciri pohon kelapa gading ini bisa ditemui di depan masjid pesantren Ringinagung, desa Keling, kecamatan Kepung.
Ketiga, balekambang. Bagian depan dari rumah joglo ini digunakan sebagai tempat pengajaran agama, pertemuan sampai sarasehan. Ciri balekambang ini bisa ditemui pada rumah Soenartono, cicit pasukan Diponegoro yang menetap di desa Ngetrip, kecamatan Mojo.
Keempat, kolah. Kolam air yang digunakan untuk berwudlu atau mandi ini merujuk pada istilah fiqih: qullah, yang berarti ukuran jumlah air yang bisa digunakan untuk bersuci. Hampir di berbagai pesantren/masjid yang didirikan pasukan Diponegoro memiliki kolah. Kolah ini juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan senjata agar tidak diketahui oleh pihak kolonial.
Pesantren: Alih Strategi Perlawanan
Pasca sang pemimpin Java Oorlog itu diasingkan ke tanah seberang, para pasukan mulai menyebar dan menyembunyikan diri dari kejaran pasukan kolonial. Mereka mulai mengaburkan identitasnya dan memilih membabat hutan untuk memulai kehidupan yang baru.
Perang mungkin tak lagi berkecamuk, sebab para laskar memilih mengubah taktik perang mereka dengan merujuk pada QS. At-Taubah ayat 22. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tidak semua pasukan harus menghidupi jalan berperang secara fisik, melainkan ada medan perang lain yang disebut mengajarkan agama kepada sekitar. Meminjam bahasanya Rijal Mumazziq Z.: dari medan perang ke arena pendidikan.
Strategi tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Kiai Sai, sosok yang diyakini sebagai cikal-bakal berdirinya desa Jarak, kecamatan Plosoklaten. Kiai Sai memiliki nama asli Sambiyo. Ia mengganti namanya menjadi Sai atau Sangi, untuk mengaburkan identitasnya dari buntutan kolonial.
Kiai Sai menghentikan pelariannya dengan mendirikan masjid dan pesantren, yang akrab disebut Pondok Bendo. Pesantren ini didirikan pada medio abad ke-19. Namun sebelum mendirikan pesantren, membabat alas bukanlah hal yang mudah. Kiai Sai harus menebang pohon Bendo yang terkenal angker. Dalam menebang pohon yang kelak dijadikan toponimi dusun tersebut, kiai sai harus merapalkan doa-doa dari alquran, sampai pada pohon tersebut benar-benar berhasil tumbang.
Apa yang dilakukan Kiai Sai tak jauh beda dengan Kiai Nawawi dari desa Keling, kecamatan Kepung. Kiai Nawawi merupakan pasukan Diponegoro yang berasal dari Pati. Awalnya sang kiai menetap di desa Puhjajar, kecamatan Papar sebagai dakwah Islam, sebelum akhirnya berpindah karena tanahnya tidak memadai untuk tempat belajar.
Pada saat memutuskan berpindah, Kiai Nawawi harus melakukan babad alas desa Keling yang terkenal angker. Terdapat pohon Beringin besar yang sulit dirobohkan. Sampai pada akhirnya, Kiai Nawawi melafalkan salawat Keling dan berhasil membuka hutan tersebut. Dari peristiwa tersebut, pesnatren yang ia dirikan dinamai Ringinagung dan desa Keling.
Selain dua kiai tersebut, buku ini juga menyebutkan beberapa kiai, seperti: Kiai Ilyas di Damarwulan-Kepung; Kiai Hasan Muchyi di Kapu-Pagu; dan Kiai Sirojudin di Tertek-Pare. Tentunya nama-nama tersebut hanya sebagian kecil dari kiai-kiai ‘Diponegaran’ yang tersebar di wilayah Kediri.
Dari Bangsawan ke Pasukan
Pasukan Diponegoro bukan hanya dari kalangan ulama dan santri, melainkan dari kalangan ksatria, keraton. Hal itu sebagaimana diungkapkan Bizawie dalam Diponegoro and Ulama Nusantara Network (2020), aliansi santri-ksatria yang dibangun Diponegoro memperoleh dukungan sosial yang luas dan unik dengan semangat keagamaan.
Sosok bangsawan yang seyogyanya berada di lingkungan yang mapan, merelakan itu semua dan turun gunung ke gelanggang pertempuran. Salah satunya yaitu Eyang Panji, yang pasca 1830 harus menanggalkan pernak-pernik keratonnya untuk tinggal di pedesaan kaki gunung Kelud: desa Pojok, kecamatan Wates.
Eyang Panji berasal dari keluarga keraton Kasunanan Surakarta dengan nama asli keraton Bendoro Raden Mas (BRM) Panji Soemoadmojo. Tidak seperti dua tokoh yang disebutkan di sebelumnya, Eyang Panji tidak membangun pesantren.
Namun, Eyang Panji semasa hidupnya berjasa dalam babat alas Pojok yang terkenal dengan binatang buasnya: macan. Di lahan yang ia buka pula, Sang Proklamator Indonesia menghabiskan masa kecilnya bersama ayah angkatnya, RM. Soemosewojo, yang merupakan putra sulung dari Eyang Panji.
Tidak berbeda dengan Eyang Panji, di wilayah Tulungrejo, kecamatan Pare, terdapat juga pasukan Diponegoro yang disebut-sebut dalam catatan seorang antropolog Amerika, Clifford Geertz. Mbah Wahid namanya, yang konon berasal dari keraton Solo dengan nama Raden Mas (RM) Jalu Mampang. Ia juga membabat alas dengan cara menyembelih kerbau dan bertapa di perut kerbau.
Berbeda dengan temuan data Mas Fikri, Geertz dalam Religion of Java menyebutkan Mbah Nur Wakit berasal dari keraton Yogyakarta. Raja Bragang menghadiahinya wilayah yang disebut dengan Sumbersari. Mbah Nur Wakit kemudian mengitari batas wilayah tersebut dan muncul topan yang membabat habis hutan. Namun, apakah Mbah Wahid/Nur Wakit ini mengacu pada sosok yang sama antara satu sama lain, tentunya perlu penelitian lebih lanjut.
–
Topik mengenai Diponegoro akan selalu menarik untuk dikaji, bukan hanya ihwal laku terjang sang pangeran dalam De Java Oorlog, tetapi juga para pasukannya yang telah menyebar di berbagai wilayah. Upaya Mas Fikri dalam merangkai tradisi lisan dalam buku ini turut memperkaya khazanah kajian pasukan Diponegoro pada skala lokal, lebih kecil lagi pada tingkat desa/dusun, yang bahkan mungkin seorang Peter Carey pun terbatas atas itu.
Tentunya tokoh-tokoh yang dihadirkan dalam buku ini masih belum keseluruhan dari pasukan Diponegoro yang ada di Kediri. Barangkali keterbatasan ruang dan waktu membuat Mas Fikri tak sempat menuliskan keseluruhannya dalam buku. Atau malah jejak-jejaknya masih senantiasa menyembunyikan identitasnya di dalam bilik langgar-langgar kecil, di bawah rindangnya pohon sawo kecik.
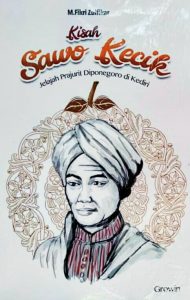 Judul Buku : Kisah Sawo Kecik: Jelajah Prajurit Diponegoro di Kediri
Judul Buku : Kisah Sawo Kecik: Jelajah Prajurit Diponegoro di Kediri
Penulis : M. Fikri Zulfikar
Penerbit : Growin (2019)
Jumlah Hlm. : 170 hlm.
ISBN : 978-602-73564-5-0